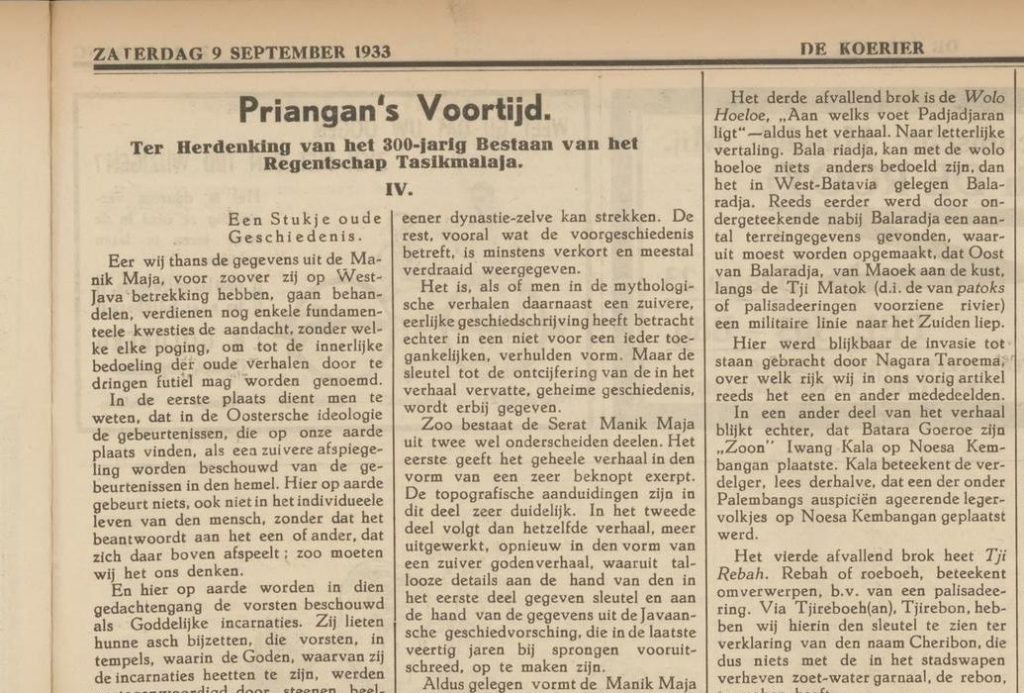Artikel di harian umum Koerier, 9 September 1933. Dengan judul asli Priangan’s Voortijd.
Ter HerdenKinfl van nei auu-iarig nesiaan van «ei Regentschap Tasikmalaja. IV. Artikel yang ditulis untuk mengenang tahun pertama pemerintahan Tasikmalaya. Beberapa penamaan geografis masih menggunakan ejaan lama, namun merujuk kepada nama yang sama.
Sedikit sejarah. Sebelum kita membahas data dari Manik Maja, sejauh berkaitan dengan Jawa Barat, beberapa hal mendasar patut diperhatikan. Tanpanya, upaya apa pun untuk memahami makna terdalam kisah-kisah kuno ini akan dianggap sia-sia. Pertama, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Timur, peristiwa yang terjadi di bumi kita dianggap sebagai refleksi murni dari peristiwa di surga. Di bumi, tidak ada yang terjadi, bahkan dalam kehidupan individu manusia, tanpa berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di sana; begitulah seharusnya kita memandangnya. Dan di bumi, dengan cara berpikir ini, para penguasa dianggap sebagai inkarnasi dewa. Abu mereka disemayamkan di kuil-kuil, di mana para dewa, yang seharusnya merupakan inkarnasi mereka, diwakili oleh patung-patung batu yang dibentuk sesuai dengan karakter mereka sendiri. Bahkan selama masa hidup mereka, mereka pun membiarkan penghormatan ilahi dianugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, jika dalam kisah mitologi seperti Manik Maja, seorang dewa bernama Wisnu mengidentifikasikan dirinya dengan seorang Prabhu Mangoekoehans dari Mendang Kamoelan, dan permaisurinya Dewi Sri dengan permaisurinya Dewi Dharmmanastiti, maka kita sedang berhadapan dengan tokoh-tokoh sejarah dari pasangan kerajaan yang tinggal di Mendang Kamoelan. Masih banyak lagi yang perlu dijelaskan, tetapi akan dibahas lebih lanjut di lain waktu. Candi-candi, tempat para pangeran pertama-tama menerima penghormatan ilahi kepada patung mereka, dan kemudian juga kepada abu mereka, pada dasarnya merupakan gambaran Gunung Suci: poros bumi, tempat Dewa bersemayam. Dan dalam hal ini, candi Jawa, yang pada dasarnya terdiri dari tumpukan tiga dadu yang semakin kecil, merupakan piramida berundak, yang merujuk pada “rumah”, “Gunung” Dewa. Nah, jika kita tahu bahwa kediaman pangeran, seperti Majapahit, terdiri dari pura persegi, di mana istana kerajaan berdiri di utara alun-alun pusat, dan di selatannya terdapat kediaman para pendeta tinggi. Dan bahwa di sudut-sudut alun-alun ini terdapat tempat-tempat suci, sementara di tengah setiap sisinya dibangun rumah-rumah alun-alun yang berdinding dan tertutup, maka jelaslah bahwa tata letak yang teratur ini tidak lain adalah esensi yang sama yang digambarkan sebagai istana suci di candi-candi Jawa, dengan sudut-sudutnya yang cekung dan menonjol, dihiasi dengan monumen-monumen di atas cornice. Kemiripan itu menjadi lebih mencolok ketika kita mempertimbangkan bahwa pusat kota yang disebutkan di sini dikelilingi oleh area-area permukiman tertentu di semua arah, seperti pasar dengan tempat tinggal para pedagang di utara; kawasan Ciwaite di timur; kawasan Buddha di selatan; dan kawasan keluarga kerajaan di barat. Kompleks-kompleks tempat suci yang besar pada diagonal-diagonalnya melengkapi keseluruhannya menjadi sebuah bentuk yang teratur.Majapahit Raya ini kembali dikelilingi hingga ke empat titik mata angin oleh empat wilayah pinggiran kota, yang masing-masing berukuran sama dengan pusat kota, sementara keseluruhannya kembali dibentuk menjadi bentuk yang teratur oleh berbagai pusat militer dan keagamaan. Dengan demikian, kota ini tampak seperti candi raksasa tiga dimensi, di mana berbagai sabuknya tidak dibangun di atas satu sama lain, melainkan—untuk membentuk keseluruhan yang tangguh dari perspektif pertahanan—diatur mengelilingi satu sama lain. Kota Hunian ini, tempat tinggal semua pengikut dan pejabat, merupakan cerminan mikrokosmik murni dari bentuk yang membentuk seluruh negara Hindu secara makrokosmik. Kota ini, sebagai pusat Kekaisaran, dan juga Kekaisaran dengan seluruh organisasinya, dengan demikian dianggap sebagai Gunung Suci, tempat suci par excellence, tempat bersemayamnya inkarnasi Dewa tertinggi di bumi: Sang Pangeran, dikelilingi oleh para Dewa yang lebih rendah: para pengikutnya. Siapa pun yang memahami hal ini akan mudah memahami kitab seperti Manik Maja. * Buku ini menyajikan sejarah murni, meskipun dalam bentuk yang terselubung mitologi. Pada zaman dahulu, bentuk historiografi lain memang dikenal di Jawa: babad, atau kronik. Namun, babad-babad tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Mereka hanya menyajikan bagian sejarah yang kondusif bagi kehormatan dan kejayaan.
sebuah dinasti itu sendiri. Sisanya, terutama yang berkaitan dengan prasejarah, setidaknya disingkat dan biasanya disajikan dengan cara yang terdistorsi. Seolah-olah, selain kisah-kisah mitologis, seseorang telah mencoba menulis sejarah yang murni dan jujur, meskipun dalam bentuk terselubung yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Namun, kunci untuk menguraikan sejarah rahasia yang terkandung dalam cerita tersebut diberikan bersamanya. Dengan demikian, Serat Manik Maja terdiri dari dua bagian yang berbeda. Bagian pertama menyajikan keseluruhan cerita dalam bentuk kutipan yang sangat ringkas. Indikasi topografi sangat jelas di bagian ini. Bagian kedua kemudian mengikuti cerita yang sama, lebih dielaborasi, lagi-lagi dalam bentuk cerita murni tentang para dewa, yang darinya detail yang tak terhitung jumlahnya dapat diperoleh dengan menggunakan kunci yang diberikan di bagian pertama dan data dari penelitian sejarah Jawa, yang telah berkembang pesat dalam empat puluh tahun terakhir. Dengan demikian, Manik Maja merupakan catatan lengkap tentang invasi Hindu ke Jawa, yang pasti berasal dari Sumatra Selatan (Nagara Saka di Lampong?) dan yang membangun peradaban yang begitu mengagumkan di Jawa. Secara historis, kita tahu bahwa pada Abad Pertengahan, kerajaan Sri Widjaja di Palembang dianggap sebagai saingan terbesar Jawa. Dalam Serat Manik-Maja, penaklukan Jawa terjadi melalui sekelompok “Dewa” yang berada di bawah naungan sosok Batara Guru, yang, bagaimanapun, tidak ikut serta. Ia hanya sesekali turun tangan, ketika perjuangan terancam tidak kunjung usai. Oleh karena itu, kami percaya, dan berdasarkan apa yang diketahui—secara historis!—tentang kerajaan Sri Widjaja, bahwa kita harus mengidentifikasi sosok Batara Guru ini dengan Palembang, yang di sini, di nusantara, pernah memperjuangkan supremasi absolut, yang terutama berarti supremasi atas perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ketika Batara Guru lahir, tanah Jawa belumlah “padat”—ia terombang-ambing oleh setiap angin. Artinya: belum “dikonfirmasi” di bawah kekuasaan Palembang.1 Keadaan lain lagi yang mengkhawatirkannya: bagian barat pulau itu tenggelam, sementara bagian timur “mencapai langit”, yang darinya kita memahami bahwa Jawa sedang menjalankan kebijakan perdagangan independen yang merugikan Palembang, terutama di timur, yang tidak terlalu takut dengan angkatan laut militer Palembang. Guru kemudian memanggil para penasihatnya untuk memberikan pendapat mereka tentang fenomena ini. Pendapat mereka adalah bahwa bagian barat “tenggelam” karena sebuah “gunung” yang berat berdiri di sana. “Gunung” ini harus dipindahkan ke timur. Sehubungan dengan apa yang telah kita catat di atas, jelas bahwa “gunung” ini pasti merujuk pada sebuah negara kecil di barat yang diorganisasikan menurut prinsip yang juga dianut di Majapahit. Terutama, karena para dewa,Mereka yang, atas perintah Guru, harus memindahkan “Gunung”, bersama-sama membentuk apa yang disebut Djawat Naiva Sanga. Ini adalah sistem sembilan negara, dengan seorang dewa di tengah, empat di titik mata angin, dan empat di diagonal, sebuah prinsip yang sepenuhnya dianut dalam skema arsitektur Majapahit. Menariknya, dalam kisah tersebut, Dewa Wisnu, dewa Utara, bertindak sebagai pemimpin. Para dewa kemudian mengangkat “Gunung” dan mulai memindahkannya. Di sepanjang jalan, berbagai pecahan jatuh. Pecahan-pecahan ini adalah garis dan pos militer yang ditinggalkan oleh invasi Jawa, ke mana pun ia melewatinya, untuk mengukuhkan wilayah. Pecahan pertama yang jatuh adalah gunung: Tempoorooh. Ini tak lain adalah pulau kecil Poeloe Tempoeroeng atau Toppershoedje, yang merupakan muara utara Selat Sunda. Navigasi melalui negara tersebut dikendalikan oleh negara ini. Kemungkinan besar, tempat ini memiliki pelabuhan kecil di zaman dahulu, dan masih menjadi tempat pendaratan yang sangat cocok untuk perahu layar di sisi timur selama musim barat, dan di sisi barat tanjung yang membentang ke selatan selama musim timur. Tempat ini pastilah menjadi pangkalan angkatan laut yang menguntungkan bagi perahu layar perang Palembang, yang terkenal di kalangan orang Arab dan Tionghoa zaman dahulu. “Bongkahan” ini dilaporkan runtuh di lokasi “Gunung” itu sendiri. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Kekaisaran Barat terletak di Selat Sunda di sebuah pulau—yang mungkin sekarang telah lenyap—atau di daratan Sumatra: Nagara Saka dalam bahasa Lampung kemungkinan yang dimaksud. Bongkahan runtuh kedua adalah “Gunung” Tjaringin. Tjaringin ini masih ada; terletak di dekat pelabuhan terbaik Jawa di Selat Sunda: Laboean. Oleh karena itu, pendaratan di Jawa terjadi di Tjaringin.Bahwa Kekaisaran Barat terletak di Selat Sunda di sebuah pulau—yang mungkin kini telah lenyap—atau di daratan Sumatra: kemungkinan yang dimaksud adalah Nagara Saka dalam bahasa Lampung. Bagian kedua yang hilang adalah “Gunung” Tjaringin. Tjaringin ini masih ada; terletak di dekat pelabuhan terbaik Jawa di Selat Sunda: Laboean. Jadi, pendaratan di Jawa terjadi di Tjaringin.Bahwa Kekaisaran Barat terletak di Selat Sunda di sebuah pulau—yang mungkin kini telah lenyap—atau di daratan Sumatra: kemungkinan yang dimaksud adalah Nagara Saka dalam bahasa Lampung. Bagian kedua yang hilang adalah “Gunung” Tjaringin. Tjaringin ini masih ada; terletak di dekat pelabuhan terbaik Jawa di Selat Sunda: Laboean. Jadi, pendaratan di Jawa terjadi di Tjaringin.
Fragmen ketiga yang hilang adalah Wolo Hoeloe, “Di kaki gunung yang terletak Padjadjaran”—begitulah ceritanya. Terjemahan harfiahnya, Bala riadja, menunjukkan bahwa Wolo Hoeloe tidak lain merujuk pada Balaradja, yang terletak di Batavia Barat. Penandatangan sebelumnya telah menemukan sejumlah detail medan di dekat Balaradja, yang darinya disimpulkan bahwa di sebelah timur Balaradja, dari Maoek di pesisir, garis militer membentang ke selatan di sepanjang Tji Matok (yaitu, sungai yang dibatasi patok atau palisade). Rupanya, invasi di sini dihentikan oleh Nagara Taroema, yang tentangnya telah kami laporkan di artikel kami sebelumnya. Namun, bagian lain dari cerita tersebut mengungkapkan bahwa Batara Guru menempatkan “putranya” Iwang Kala di Nusa Kembangan. Kala berarti “sang penghancur”, yang berarti bahwa salah satu unit tentara kecil yang beroperasi di bawah naungan Palembang ditempatkan di Noesa Kembangan. Fragmen keempat yang jatuh disebut Tji Rebah. Rebah, atau roeboeh, berarti meruntuhkan, misalnya, pagar kayu. Melalui Tjireboeh(an), Tjirebon, kita menemukan kunci untuk menjelaskan nama Cheribon, yang karenanya tidak ada hubungannya dengan udang air tawar, rebon, yang diagungkan dalam lambang kota. Nama kelima dan keenam tidak menyebutkan pecahan-pecahan yang berjatuhan, melainkan banyak pecahan yang berjatuhan seperti puing di sepanjang jalur pasukan. Mereka disebut Pragoota dan Kéndéng, dan pasti merujuk pada garis-garis militer yang luas, yang sebagiannya memang telah direbut kembali, dan yang memisahkan pedalaman Jawa dari pesisir, sehingga perdagangan mereka (beras dan kebutuhan pokok lainnya sebagai alat tukar dalam perdagangan rempah-rempah) dapat dikendalikan oleh bangsa-bangsa penjajah. Sisa cerita ini berkaitan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh karena itu, akan terlalu jauh jika kita melanjutkannya di sini, terutama karena akan muncul kesempatan untuk kembali ke cerita ini. Saat ini kita memiliki informasi yang cukup untuk Jawa Barat. Nama Pragoota dilestarikan di Bukit Bergota dekat Semarang dan sebagai Prabata, Perwata, dan Prambatan dalam rangkaian nama yang membentang dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kénding muncul sebagai nama pegunungan dari utara Wijnkoopsbaai, langsung melewati Priangan, hingga Malang selatan. Sebagian dari Noesa-Kembangan, oleh karena itu, Priangan tampaknya telah ditembus. Bahkan, di selatan Tasikmalaya, lokasi sebuah kerajaan terindikasi: Mendang Kamoelian, yang—menurut tradisi—pasti lebih tua dari Padjadjaran. Mendang Kamoelian, atau Mendang Kamoelan, kini menjadi nama kerajaan Dinasti Sandjaja, yang memainkan peran penting di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam kisah kita, “Dewa Wisnoe” tampaknya tidak merujuk pada apa pun selain Dinasti Sandjaja, yang kedudukannya terus bergeser lebih jauh ke timur. Oleh karena itu, nama-nama seperti Tji Medang di Garoet Selatan dan Sumedang di utara seharusnya tidak mengejutkan:Dari Cirebon dan Noesa Kembangan, dan mungkin juga dari Wijnkoopsbaai, Nagara Taroema diserang dari belakang dan “digulung” hingga hanya bisa bertahan di Pajajaran, yang penguasa pertamanya—seperti yang telah kita lihat—menurut dokumen batu asli dari sekitar tahun 450 M, “pada suatu ketika memerintah di Nagara Taroema.” Konteks yang disajikan di sini dalam buku ini sepenuhnya selaras dengan fakta bahwa tidak hanya di Bataraja, tetapi juga di Cirebon, Kuningan, Galoeh, Tasikmalaya, Garoet, dan Bandung, bahkan di dalam kawasan permukiman Bandung, sebelum masa ketika peraturan pengendalian wabah mengakhiri semua tradisi bangunan lokal (kegunaan langkah ini masih tampak sangat bermasalah bagi kami), bentuk-bentuk bangunan Sumatra tetap populer hingga zaman modern, bentuk-bentuk yang sama sekali tidak ada di Buitenzorg, misalnya. Bentuk-bentuk bangunan ini digambarkan dengan sangat tepat pada relief-relief Baraboedoer dan Prambanan. Hal ini juga menjelaskan supremasi yang, bahkan di kemudian hari, Sumedang dan Tasikmalaya kuasai seluruh wilayah Priangan. Dari bagian lain kisah Manikmaja, dapat disimpulkan bahwa penduduk Nagara Taroema yang bertani beremigrasi ke Jawa Tengah. Hal ini menjelaskan penemuan arca-arca bertipe Padjadjaran diGoenoeng Prabata dijelaskan dengan baik di Pekalongan. Namun, juga menjadi jelas bahwa pada zaman dahulu, Priangan dikenal sebagai wilayah pegunungan yang tertutup hutan, yang penduduknya hanya
melalui hasil hutan, perburuan, dan paling banyak melalui budidaya ladang (di atas tanah). Namun, Padjadjaran merupakan pengecualian. Ada kemungkinan juga bahwa di wilayah pegunungan, “alam orang mati” kuno, budidaya lahan biasa dan budidaya sawah, “pantang”, mungkin telah dilarang. Masyarakat penjajah, sebagai masyarakat militer pada umumnya, tidak terlalu tertarik pada pertanian. Namun, mereka bertempur dengan senjata tembaga dan baja. Oleh karena itu, Priangan Timur, khususnya, selalu dikenal dengan kerajinan tembaga dan pandai besinya, dan Sumedang, khususnya, dengan para pandai besinya. Apakah penyebaran masyarakat berbahasa Jawa di daerah-daerah terpencil di sepanjang pantai utara dan selatan Jawa Barat mungkin masih ada hubungannya dengan invasi kuno ini adalah pertanyaan yang tentu layak untuk dikaji lebih lanjut secara serius. Karakteristik rasial yang tidak biasa yang ditemui Dr. Nyessen selama penelitian antropologisnya di Priangan Selatan mungkin juga terkait. Dan siapa yang tidak teringat orang Melayu Sumatra ketika mendengar nama Tasik Malaja? Bagaimanapun, jelas bahwa asal-usul Kabupaten Tasikmalaya harus dicari di Mendang Kamoelian, yang terletak di pesisir selatan. Lebih lanjut, kerajaan kecil ini pasti telah meninggalkan tradisi yang sedemikian rupa di wilayah tersebut sehingga, pada masa Sultan Agoeng, seorang “orang Sunda” dari kabupaten ini memiliki informasi yang cukup—juga menggunakan tradisi Jawa Tengah dan Jawa Timur—untuk menulis manik maja. Goenoeng Loemboeng , di selatan Cililin, pasti pernah mendominasi Priangan Tengah sebagai donjon Hindu di tengah dataran tinggi Bandung dan Padalarang. Inventarisasi arkeologi Jawa menyebutkan sebuah bangunan bertingkat, sebuah linggam (simbol kekuasaan), dan sebuah “arca Polinesia” di bukit itu. Setelah diamati lebih dekat, arca ini sama sekali tidak bernuansa Polinesia; arca ini sangat indah, Wisnu, yang dibawa oleh seekor Garuda yang sedang terbang. Namun, tubuh bagian atas figur dewa tersebut hilang. Dewa Wisnu—seperti yang telah kita lihat—adalah pemimpin “Patung Penunggang Kuda”. MP